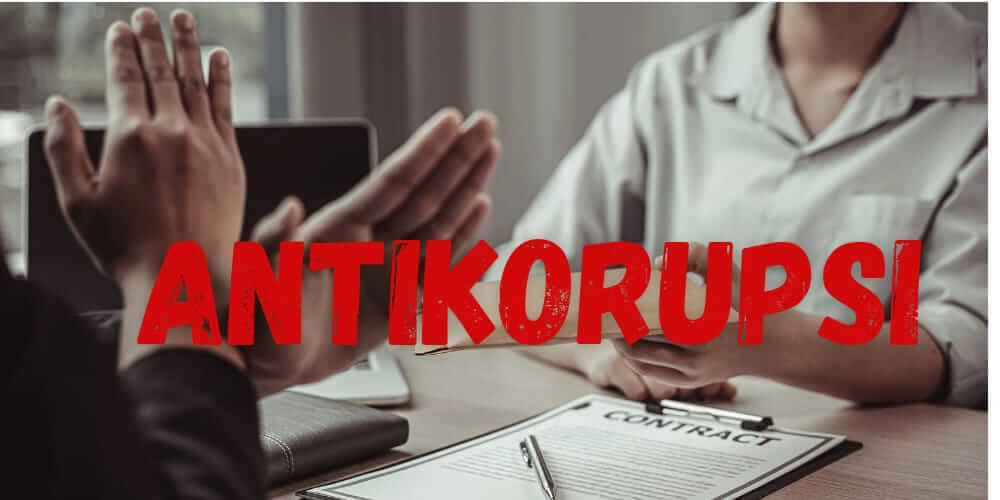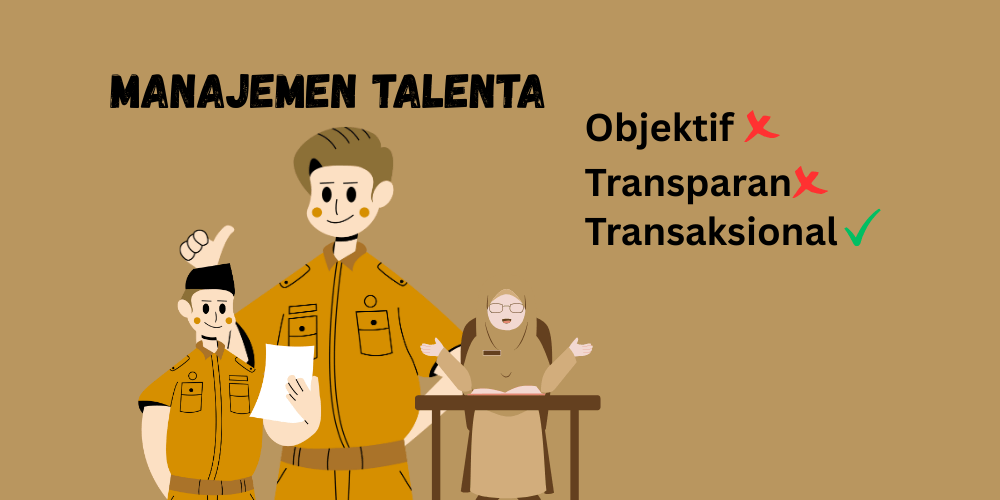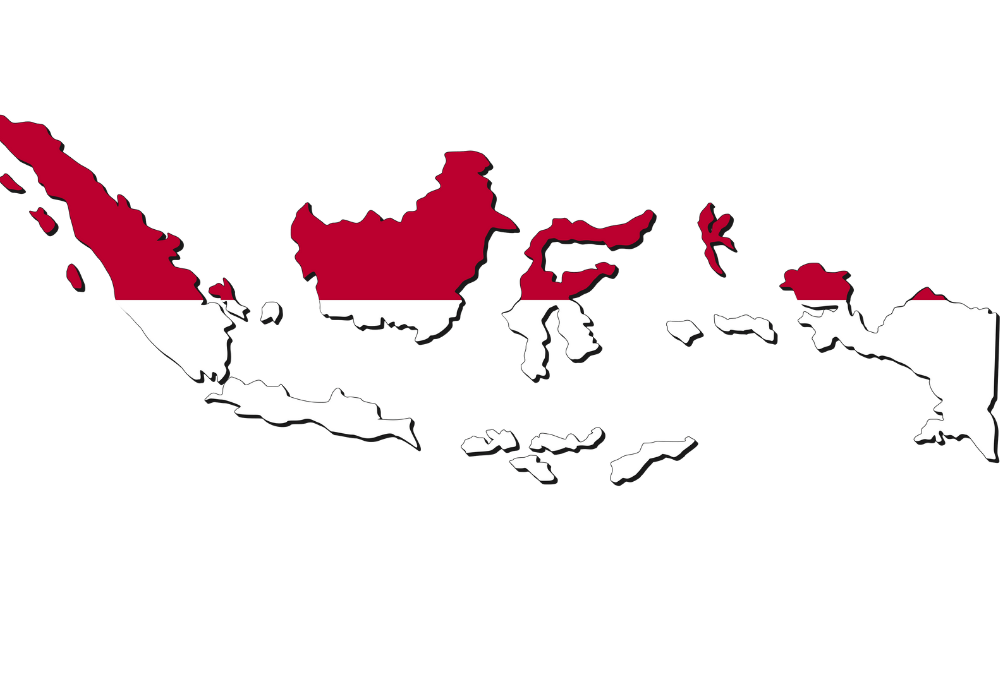Akar Praktik Koruptif di Legislatif

Praktik koruptif dalam kerja-kerja legislatif nyaris tak terendus walau tampak nyata dari kinerja mereka yang cenderung kontroversial, terutama dalam pembahasan dan penyusunan undang-undang.

Struktur kekuasaan yang legislative heavy bukannya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat malah cenderung digunakan untuk kepentingan politik sesaat. Teori klasik Robert Klitgaard merumuskan korupsi sebagai C = M + D – A, dengan C = korupsi, M = monopoli, D = diskresi (kewenangan), A = akuntabilitas. Artinya, korupsi muncul ketika kekuasaan (monopoli) dan kewenangan besar tidak diimbangi dengan pertanggungjawaban yang fuat, sangat relefan dengan kondisi legislatif kekinian.
Sistem politik yang oligarkis dan terkonsentrasi, seperti di Indonesia, memberi ruang bagi elite untuk mengendalikan lembaga dan sumber daya publik, termasuk lembaga legislatif yang memiliki kewenangan baik dalam pembuatan undang-undang maupun penyusunan anggaran negara. Kewenangan yang besar ini berpotensi disimpangkan, bekerja berdasarkan pesanan pihak luar yang punya kepentingan atas satu produk legislasi.
Sebab lain dari perilaku koruptif anggota parlemen ditengarai akibat sistem politik dan biaya politik yang tinggi, seperti mahalnya biaya kampanye, membuat para politikus tergiur bahkan mengandalkan dana yang tidak bersih. Diperparah dengan sistem partai yang tidak transparan dan proses rekrutmen yang tidak memperhatikan sistem merit yang menciptakan peluang korupsi.

Tindakan koruptif di parlemen seperti terus terjadi dan bahayanya, menjadi semacam budaya. Meminjam teori belajar sosial (Social Learning Theory – SLT), Albert Bandura menjelaskan bahwa orang belajar perilaku dan keterampilan baru melalui observasi, imitasi, dan pemodelan dari orang lain di lingkungan mereka, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Pun di parlemen, model seperti ini tengah berlangsung.
Berdasarkan teori itu, jika perilaku korup menjadi hal yang dibiarkan atau ditiru maka akan sulit diubah. Pengawasan internal, seperti oleh Badan Kehormatan DPR/DPRD, yang lemah membuat parah kondisi ini.
Modus kamuflase pembajakan anggaran seperti dana aspirasi, proyek aspirasi, dan/atau program aspirasi, dipaksakan masuk dalam kegiatan lembaga eksekutif dengan dalih kepentingan rakyat, padahal sedang menjalankan apa yang disebut Chester Collins Maxey dalam artikel National Municipal Review yang terbit 1919 sebagai politik pork barrel atau politik gentong babi.
Politik gentong babi menjadi strategi politikus guna menggunakan dana publik dalam jumlah besar untuk proyek-proyek lokal di daerah pemilihan mereka demi mengamankan dukungan pemilih dan membantu mereka terpilih kembali. Jadi, sejak dilantik, politikus ini sudah berpikir bagaiamana agar terpilh kembali.
Dalam buku Wajah Korupsi di Indonesia, ditemukan analisis perilaku korupsi berupa praktik jual-beli pasal dalam pembentukan undang-undang, termasuk konflik kepentingan dan kurangnya transparansi—sehingga perlu pengawasan publik dan perlindungan whistleblower. Tulisan artikel dalam buku itu mengungkap analisis Analisis Kasus Revisi Undang-Undang Bank Indonesia dan Keterlibatan Bank Indonesia yang melibatkan petinggi Bank Indonesia atas dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia tahun 2004. Kasus itu memberikan fakta hukum bahwa terdapat aliran dana kepada DPR komisi IX periode 2003 yang merupakan panitia perbankan untuk penyelesaian masalah Bantuan Likiuditas Bank Indonesia dan amandemen UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Juga dikupas analisis kasus Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang terhitung hanya 13 hari dari total semua tahap pembentukan, mulai dari proses awal pengusulan Rancangan Undang-Undang hingga kepada pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Salah satu kejanggalan dari sisi formil yang dilakukan DPR dalam merevisi Undang-Undang KPK adalah ternyata UU KPK bukan menjadi program legislasi nasional prioritas di tahun 2019, kemudian inisiatif DPR untuk revisi UU KPK hanya dihadiri 70 orang, yang tidak memenuhi syarat, serta tidak menyertakan naskah akademik terbaru. Hingga kepada rapat pembahasan yang singkat dilakukan pada malam hari, tanpa melibatkan publik, terutama kelembagaan dan struktur KPK sebagai objek pembahasan yang terdapat dalam revisi Undang-Undang tersebut (Detik News, 2019. Adi, 2020). Kacaunya, proses perumusan dan pembahasan yang singkat tidak melibatkan KPK.
Lalu, proses pembentukan Undang-Undang (Omnibus Law) Cipta Kerja, yang diusulkan Presiden Jokowi pada Oktober tahun 2019. Dalam hal ini DPR dan Pemerintah, sudah melakukan pertimbangan untuk menggunakan metode Omnibus dalam sistem hukum di Indonesia. Proses legislasi RUU usulan pemerintah tersebut disahkan pada September 2020, dengan beberapa kontroversi dengan beberapa kejanggalan di antaranya keterbukaan informasi mengenai draft UU yang tidak jelas sehingga membingungkan masyarakat, termasuk juga ahli yang ingin mengkaji, dan pihak terkait yang terdapat dalam objek pembentukan UU Cipta Kerja. Pasca pengesahan, terdapat perubahan dan pengurangan pasal.
Pekerjaan DPR bersama Pemerintah, untuk mengesahkan UU Cipta Kerja ini juga terkesan terburu-buru hingga mengambil waktu libur akhir pekan untuk rapat di luar gedung dan mengesahkan ketika malam hari.
Lalu apa dampaknya bagi rakyat? Dampaknya nyata dan berlapis korupsi legislatif adalah merusak kualitas undang-undang, memperlemah pemerintahan, memboroskan anggaran, dan melemahkan kepercayaan publik. Tegasnya, ini bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi serangan sistemik terhadap demokrasi dan pembangunan.
Kita harus sepakat bahwa korupsi di lembaga legislatif bukan sekadar perilaku individu, melainkan produk sistemik: struktur politik yang rapuh, kultur birokrasi yang permisif, dan minimnya akuntabilitas. Mengatasi korupsi berarti memperbaiki institusi, memperkuat kontrol sosial, dan membangun budaya politik yang bersih.
Untuk mencegah penyimpangan dalam proses legislasi maka beberapa al yang perlu dilakukan adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas bahwa setiap tahap proses legislasi harus dapat diakses oleh publik. Hal ini termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rancangan undang-undang (RUU), catatan rapat, serta hasil keputusan yang diambil. Negara-negara seperti Singapura atau negara-negara Skandinavia, telah menerapkan transparansi dalam setiap tahap legislatif mereka.
Langkah pencegahan lainnya adalah penguatan pengawasan internal dan eksternal dengan membentuk komite pengawas anti-korupsi yang independen dan bebas dari tekanan politik. Juga, pengawasan eksternal seperti KPK atau oleh masyarakat melalui organisasi non-pemerintah sangat penting.
Penegakan kode etik dan sanksi yang tegas serta konsisten dan tidak pandang bulu terhadap anggota legislatif yang terlibat dalam praktik koruptif, termasuk hukuman pidana atau pemecatan dari jabatan jika terbukti bersalah. Serta meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, seperti melalui forum publik, konsultasi, atau penggunaan teknologi untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses ini dapat menjadi pengawas yang efektif dan mengurangi ruang bagi korupsi.
Tak kalah penting, reformasi pembiayaan politik dilakukan dengan cara yang transparan, dengan aturan yang jelas tentang siapa yang bisa mendanai kampanye dan berapa jumlahnya. Pembiayaan yang tidak jelas sering menjadi sumber utama praktik suap dan korupsi.
Praktik koruptif di legislatif bisa dicegah melalui kombinasi transparansi, pengawasan yang efektif, pendidikan etika, serta sanksi yang tegas. Pendekatan ini harus diterapkan secara konsisten dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan sistem legislasi yang bersih dan akuntabel. (**)